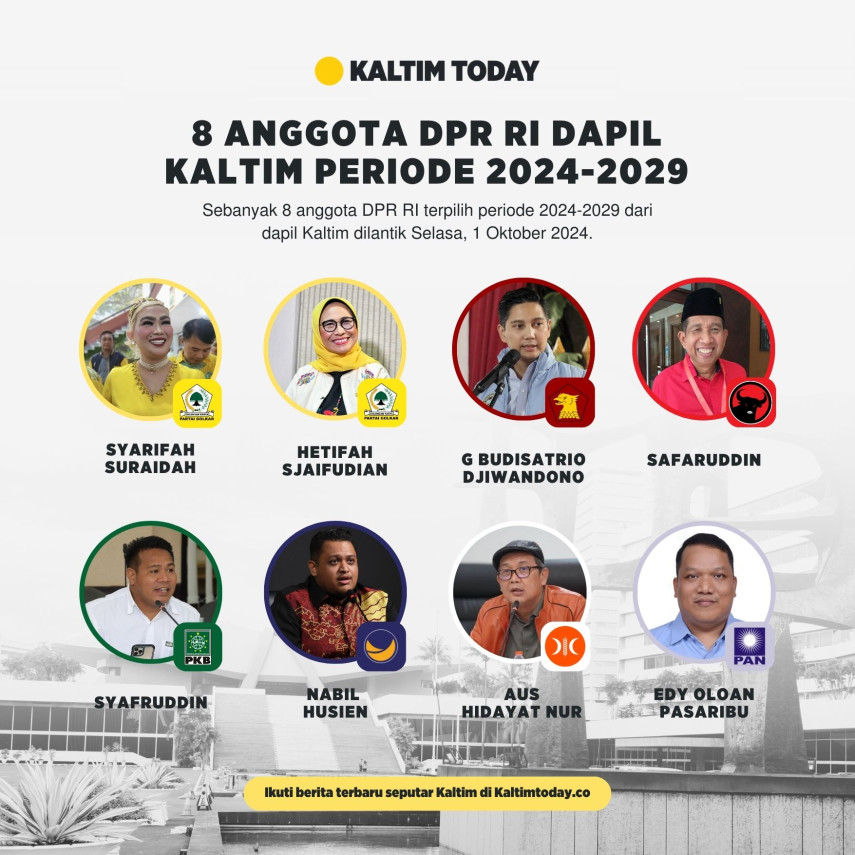Opini
Imajinasi: Dari Fondasi Bangsa ke Jalan Masa Depan

Oleh: Eko Ernada (Dosen Hubungan Internasional di Universitas Jember)
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka adalah capaian sejarah yang tidak hanya diukur lewat angka, tetapi juga lewat daya imajinasi yang membawanya sampai di titik ini. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia lahir bukan karena garis-garis geografis semata, melainkan karena imajinasi kolektif.
Benedict Anderson dalam karya klasiknya Imagined Communities menekankan bahwa bangsa adalah komunitas terbayang, dibentuk oleh keyakinan bersama meskipun anggotanya tidak saling mengenal. Imajinasi itulah yang menyatukan ratusan etnis, bahasa, dan budaya dalam satu rumah bernama Indonesia.
Namun, imajinasi bukanlah urusan masa lalu semata. Masa depan juga memerlukan daya bayang yang berani. Di sini, kita bisa belajar dari Isaac Asimov, penulis fiksi ilmiah yang mengajarkan bahwa membayangkan masa depan adalah cara manusia mendefinisikan arah peradabannya. Asimov melalui Foundation Series misalnya, berbicara tentang psikohistori: suatu ilmu yang mampu meramalkan alur peradaban melalui pola kolektif manusia. Gagasan itu, meski fiksi, menunjukkan bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi dibangun oleh visi bersama.
Indonesia hari ini berada di persimpangan antara capaian dan tantangan. Di satu sisi, kita berhasil mengonsolidasikan demokrasi, mencatat pertumbuhan ekonomi, dan memainkan peran diplomatik yang semakin diakui. Pada 2024 lalu, Indonesia tumbuh 5,05 persen, termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah World Water Forum di Bali, memperlihatkan peran global dalam isu lingkungan. Di tingkat kawasan, diplomasi Indonesia di ASEAN masih berperan kunci dalam menjaga stabilitas Laut Cina Selatan sekaligus mendorong integrasi ekonomi digital ASEAN.
Namun, tantangan nyata tetap menanti. Gini ratio 2025 masih 0,388, menunjukkan ketimpangan desa-kota yang belum tertutup. Krisis iklim makin nyata: banjir besar di Demak dan Kudus awal 2024 menenggelamkan ribuan rumah, memperlihatkan rapuhnya infrastruktur menghadapi perubahan iklim.
Ketergantungan pada batu bara masih dominan meski ada komitmen net zero emission 2060. Disrupsi teknologi juga hadir: kecerdasan buatan generatif mulai masuk ruang kelas dan birokrasi, tetapi regulasi masih tertinggal, sementara survei ILO (2024) memperkirakan 60 persen pekerjaan di Asia Tenggara berisiko otomatisasi dalam dua dekade mendatang—Indonesia tentu tidak terkecuali.
Di sinilah imajinasi menjadi penting: apakah kita akan terjebak nostalgia masa lalu, atau berani menatap masa depan dengan keberanian seperti yang dibayangkan Asimov?
Kita memerlukan “imajinasi Indonesia 2045” yang setara dengan imajinasi kemerdekaan 1945. Jika Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, maka tantangan kita sekarang adalah membentuk imagined future—masa depan bersama yang disepakati lintas generasi. Sebab, tanpa visi kolektif, perjalanan menuju seratus tahun kemerdekaan hanya akan diisi oleh pragmatisme jangka pendek yang mudah diguncang krisis.
“Imajinasi Indonesia 2045” bukan sekadar slogan politik, tetapi arah pembangunan yang menyatukan harapan rakyat. Bayangkan sebuah Indonesia yang pada usia seabad merdeka berhasil keluar dari middle income trap dan benar-benar menjadi ekonomi besar dunia, dengan pertumbuhan inklusif yang mengurangi ketimpangan desa-kota. Bayangkan pula Indonesia yang mampu memimpin transisi energi hijau: membangun jaringan listrik nasional berbasis tenaga surya, panas bumi, dan angin sehingga kemandirian energi tercapai tanpa lagi bergantung pada batu bara.
Dalam bidang sosial, imajinasi Indonesia 2045 adalah tentang membentuk generasi emas yang bukan hanya cerdas secara digital, tetapi juga berkarakter humanis. Sistem pendidikan tidak lagi sekadar mengejar angka ujian, melainkan menumbuhkan kreativitas, nalar kritis, dan daya empati—membentuk warga global yang tetap berakar pada budaya Nusantara.
Upaya pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar bisa dibaca sebagai bagian dari imajinasi itu: membangun generasi sehat sejak dini agar bonus demografi tidak terbuang sia-sia. Namun, imajinasi semacam ini harus diiringi desain yang berkelanjutan dan adil. Tanpa tata kelola yang transparan, distribusi yang merata, serta kesinambungan pendanaan, program semacam MBG berisiko menjadi sekadar retorika politik jangka pendek, bukan investasi jangka panjang.
Dalam ranah pembangunan infrastruktur dan tata kota, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dibaca sebagai upaya membayangkan pusat peradaban baru yang modern dan berkelanjutan. Namun, kritik muncul terkait dampak ekologis, pembiayaan, dan kemampuan daerah menyesuaikan diri. Tantangan ini menegaskan bahwa imajinasi 2045 harus selalu diiringi analisis risiko, agar inovasi tidak berubah menjadi beban sosial atau lingkungan.
Dalam bidang teknologi, imajinasi 2045 berarti Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar aplikasi asing, melainkan pusat inovasi di Asia Tenggara. Kota-kota besar menjadi living labs teknologi ramah lingkungan, sementara desa-desa menjadi pusat inovasi pertanian berkelanjutan berbasis kecerdasan buatan dan internet of things. Di bidang energi, program transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah contoh konkret ambisi 2045, tetapi masih menghadapi tarik menarik dengan industri batu bara yang dominan.
Dalam geopolitik, imajinasi 2045 adalah Indonesia yang mampu memainkan peran sebagai bridge builder dalam rivalitas global. Dengan posisi strategis di Indo-Pasifik, Indonesia bisa mengartikulasikan diplomasi “jalan tengah” yang bukan hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memperjuangkan tata dunia yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.
Singkatnya, imajinasi 2045 adalah tentang Indonesia yang bermartabat: maju tanpa kehilangan jati diri, modern tanpa meninggalkan solidaritas sosial, global tanpa tercerabut dari akar lokal.
Dalam konteks ini, fiksi ilmiah bukan sekadar hiburan. Ia adalah laboratorium ide. Asimov membayangkan kolonisasi ruang angkasa, kecerdasan buatan, dan sistem sosial baru. Indonesia bisa mengambil semangat serupa: berani membayangkan sistem pendidikan yang adaptif pada era digital, energi hijau yang menopang kemandirian, atau kota-kota cerdas yang humanis. Imajinasi bukan berarti melayang tanpa pijakan, melainkan memberi arah bagi kebijakan dan inovasi.
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka harus kita rayakan bukan hanya dengan retrospeksi, tetapi juga dengan proyeksi. Kita perlu bertanya: bangsa macam apa yang ingin kita bayangkan di seratus tahun kemerdekaan nanti? Apakah bangsa yang hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, atau bangsa yang menciptakan sendiri narasi masa depannya?
Seperti kata Asimov, masa depan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang kita bentuk dengan imajinasi dan tindakan. Dan seperti kata Anderson, bangsa ini hanya ada karena kita mau terus membayangkannya bersama. Maka, Indonesia butuh keberanian untuk menjadikan imajinasi sebagai energi politik, sosial, dan kultural.
Delapan puluh tahun lalu, imajinasi tentang kemerdekaan melahirkan republik. Delapan puluh tahun ke depan, imajinasi tentang masa depan akan menentukan apakah republik ini sekadar bertahan, atau benar-benar bermartabat.(*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Pemprov Kaltim Gelar Rapat Final Persiapan HUT ke-80 RI, Pastikan Semua Siap untuk Momen Bersejarah
- Lomba Melamun Jadi Daya Tarik Perayaan HUT RI ke-80 di Muara Kaman Ulu
- Pemprov Kaltim Kobarkan Semangat Nasionalisme Lewat Pembagian 7.000 Bendera Merah Putih
- Pemkot Balikpapan Minta Warga Tak Kibarkan Bendera One Piece Saat HUT RI: Kita Hidup di Dunia, Nggak Ada yang Bebas
- Rayakan HUT ke-80 RI dengan 10 Ide Kegiatan Seru, Edukatif, dan Penuh Makna