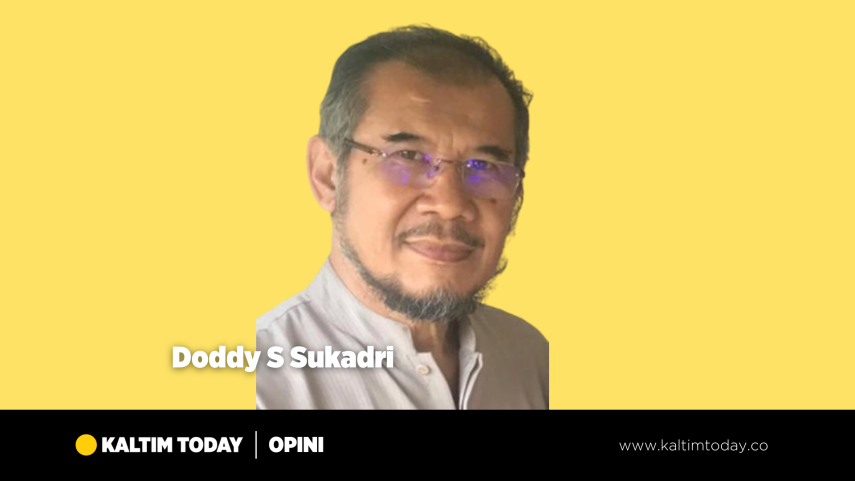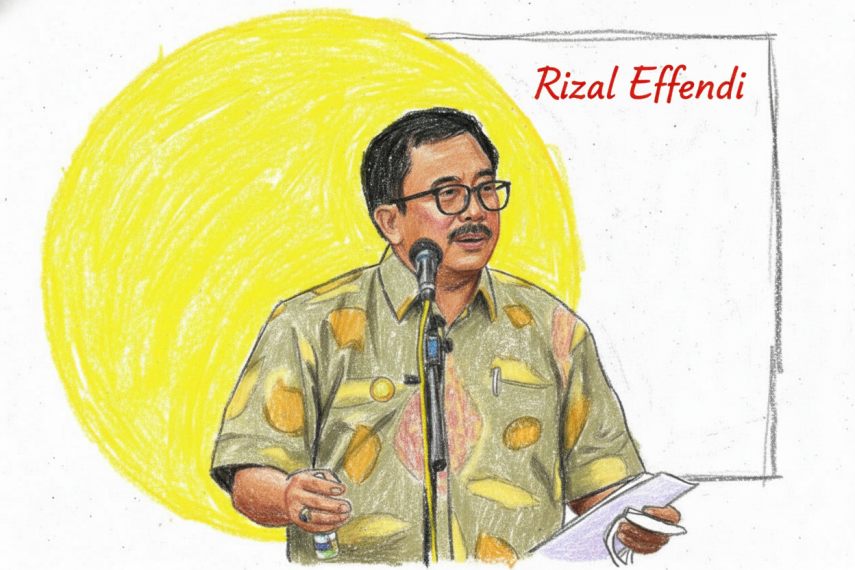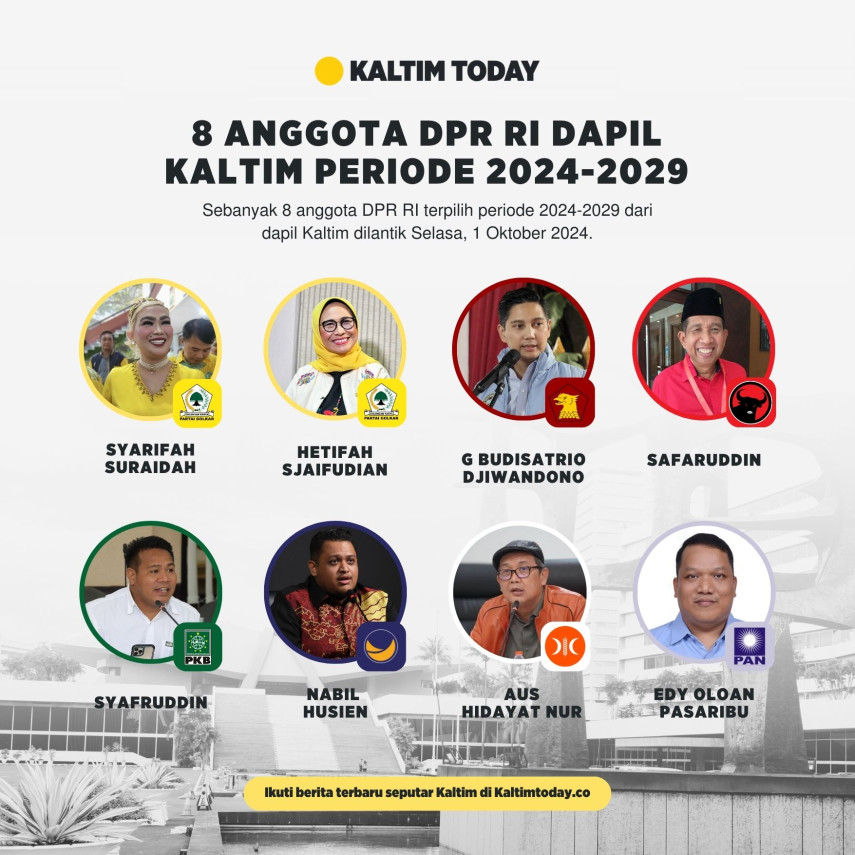Opini
Antara Pelayanan dan Kekuasaan: Kritik atas Budaya Birokrasi dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia

Oleh: Alya Nur Fitriyana, Mahasiswi Prodi Administrasi Publik, FISIP Unmul Angkatan 2023.
Budaya birokrasi di Indonesia merupakan fenomena yang sangat kompleks dan telah lama menjadi bagian integral dari tata pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi atau aturan formal, tetapi juga menyangkut nilai, norma, kebiasaan, dan pola pikir yang membentuk perilaku pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks reformasi pelayanan publik, birokrasi kerap menghadapi dilema antara menjalankan fungsi pelayanan yang efektif dan mempertahankan kekuasaan atau kepentingan politik tertentu.
Kontradiksi ini terlihat baik pada tingkat kebijakan maupun dalam praktik sehari-hari, di mana tujuan ideal birokrasi seringkali bertabrakan dengan budaya lama yang masih mengakar kuat. Budaya birokrasi yang demikian tidak hanya memengaruhi cara kerja birokrat, tetapi juga secara signifikan menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, kritik terhadap budaya birokrasi menjadi elemen penting untuk memahami hambatan-hambatan reformasi dan merumuskan strategi agar birokrasi benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekadar instrumen politik.
Selama lebih dari dua dekade reformasi pelayanan publik digulirkan, perubahan nyata dalam budaya birokrasi masih berjalan lambat. Birokrasi Indonesia masih sarat dengan pola pikir hierarkis, otoriter, dan feodal yang diwariskan sejak masa kolonial. Pola pikir ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan yang sangat terpusat hingga cara pegawai menilai posisi dan statusnya dalam organisasi.
Pegawai birokrasi sering lebih mementingkan keamanan posisi dan kepentingan pribadi daripada inovasi dan pelayanan proaktif. Resistensi terhadap perubahan menjadi fenomena umum; pegawai cenderung bertahan dalam zona nyaman, menghindari risiko, dan menolak praktik baru yang dianggap mengancam privilese mereka. Akibatnya, berbagai program reformasi, termasuk digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan transparansi, sering mengalami hambatan dan implementasinya tidak maksimal.
Salah satu masalah utama dari budaya birokrasi yang ada adalah prioritas yang lebih condong kepada kekuasaan dibandingkan pelayanan. Birokrasi cenderung menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik dan sering mengutamakan kepentingan pejabat atau elite politik daripada kebutuhan masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, keputusan yang diambil lebih berorientasi pada pelestarian hubungan kekuasaan dan mempertahankan jabatan daripada meningkatkan kualitas layanan publik.
Kondisi ini mendorong terjadinya praktik-praktik yang mengaburkan profesionalisme, termasuk nepotisme, kolusi, dan korupsi yang kerap muncul dalam proses pelayanan. Ketika masyarakat merasakan ketidakadilan, ketidaktransparanan, dan lambannya layanan, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun, sehingga jalan reformasi yang bertumpu pada pelayanan profesional menjadi lebih sulit.
Budaya birokrasi lama juga tercermin dalam praktik layanan yang lamban, birokratis, dan berbelit-belit. Masyarakat yang mengurus administrasi di kantor pemerintahan sering menghadapi sikap arogansi, ketidakpedulian, dan kurang ramah dari pegawai. Hal ini menimbulkan stigma negatif yang sulit dihapuskan meskipun pelatihan dan digitalisasi telah diterapkan.
Misalnya, meskipun layanan online dan sistem informasi manajemen sudah ada, masyarakat masih merasakan birokrasi berjalan lamban dan rumit karena pegawai belum sepenuhnya mengubah pola pikir dan budaya kerja mereka. Akibatnya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah, dan kepercayaan terhadap birokrasi belum sepenuhnya pulih.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kapasitas dan kompetensi pegawai birokrasi. Banyak pegawai yang belum mendapatkan pelatihan atau pembinaan berkelanjutan sehingga sulit beradaptasi dengan tuntutan reformasi modern, termasuk digitalisasi pelayanan publik. Ketidakmampuan mengoperasikan teknologi informasi membuat program e-government atau sistem pengaduan masyarakat hanya terlihat dari sisi alat, tanpa menghasilkan perubahan substansial dalam kualitas layanan. Selain itu, tumpang tindih peraturan dan kompleksitas birokrasi memperberat pelaksanaan reformasi. Birokrasi yang seharusnya memudahkan masyarakat justru kadang menjadi penghalang karena prosedur yang berbelit, aturan yang saling tumpang tindih, dan koordinasi antar instansi yang lemah.
Fenomena ini menciptakan paradoks sistemik dalam birokrasi Indonesia. Di satu sisi, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima harus dijalankan. Di sisi lain, birokrasi sering menjadi arena perebutan kekuasaan dan mempertahankan kepentingan partikular. Rekrutmen, promosi jabatan, dan distribusi anggaran tidak selalu berbasis meritokrasi, melainkan pada politik patronase. Hal ini berpotensi menimbulkan perilaku korup dan kolusif yang sistemik, sekaligus menghambat tercapainya pelayanan publik yang profesional. Reformasi birokrasi yang efektif harus mampu menggeser budaya kekuasaan ini menjadi budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebagai contoh konkret, masyarakat yang ingin mengurus administrasi kendaraan di SAMSAT kerap mengalami pengalaman yang berliku. Beberapa warga mengeluhkan antrean yang panjang, persyaratan yang membingungkan, dan sikap pegawai yang kurang ramah. Meskipun pemerintah kabupaten/kota telah mengimplementasikan sistem antrian online dan layanan digital untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan, masyarakat masih harus menghadapi prosedur manual di beberapa tahap, seperti verifikasi dokumen fisik dan pengecekan kendaraan.
Banyak warga merasa frustrasi karena meskipun teknologi tersedia, perilaku birokrasi lama masih mendominasi, sehingga reformasi digital belum sepenuhnya mengubah kualitas pelayanan. Kasus ini menunjukkan bahwa transformasi birokrasi tidak cukup dengan alat digital, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya dan pola pikir pegawai agar benar-benar fokus pada kepentingan publik.
Meski demikian, ada indikasi perubahan positif, terutama dengan masuknya generasi birokrat baru yang lebih melek digital dan memiliki orientasi pelayanan yang lebih tinggi. Pemerintah mendorong berbagai program reformasi, seperti penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Sistem pengaduan berbasis teknologi, e-government, dan program satu data Indonesia menjadi sarana untuk mempermudah akses masyarakat sekaligus mendorong kontrol sosial terhadap birokrasi. Dengan meningkatnya keterbukaan dan partisipasi publik, diharapkan birokrasi perlahan bergerak dari budaya kekuasaan menuju pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Reformasi pelayanan publik bukan hanya soal struktur organisasi atau penggunaan teknologi, tetapi juga soal revolusi budaya. Pola pikir, etika kerja, dan paradigma hubungan antara birokrat dan masyarakat harus diubah secara mendasar. Birokrat harus menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau politik.
Hal ini menuntut komitmen kuat, pembinaan berkelanjutan, dan regulasi yang menekankan pelayanan sebagai prioritas utama. Transformasi ini bukan sekadar idealisme, tetapi kebutuhan nyata untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, efisien, dan responsif.
Secara keseluruhan, kritik terhadap budaya birokrasi di Indonesia menegaskan pentingnya memutus ketergantungan birokrasi pada politik kekuasaan dan mengembalikan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat. Reformasi birokrasi harus menempatkan pelayanan publik sebagai tujuan utama, bukan sekadar alat pengelolaan kekuasaan.
Hanya dengan begitu, perubahan yang dilakukan akan memiliki dampak nyata bagi masyarakat, menghadirkan layanan publik yang efektif, adil, dan memuaskan. Birokrasi yang kembali ke akar filosofinya sebagai pelayan negara akan menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan contoh kasus di Tarakan, terlihat bahwa upaya reformasi tidak bisa hanya berupa kebijakan atau teknologi, tetapi harus menembus hingga perilaku, budaya, dan pola pikir birokrat. Tanpa revolusi budaya yang nyata, reformasi pelayanan publik akan tetap menjadi wacana yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, transformasi birokrasi menjadi budaya pelayanan yang profesional, efisien, dan responsif bukan sekadar aspirasi, tetapi kebutuhan mendesak bagi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan publik di Indonesia.
[RWT]
Related Posts
- Inspektorat Luruskan Temuan Perjadin DPRD Samarinda: Hanya Administratif, Tidak Ada Kerugian Negara
- Komisi III Soroti Akar Masalah Banjir, PUPR Diminta Perkuat Infrastruktur Dasar 2026
- Pemprov Kaltim Dorong Perusda Kelola Penggolongan Jembatan Sungai Mahakam
- Polisi Masih Dalami Motif Dugaan Penikaman di Jalan Otto Iskandardinata.
- Persoalan Estetika Bangunan, Dinas PUPR Samarinda Akui Belum Pertimbangkan Kemungkinan Tempias Hujan di Pasar Pagi