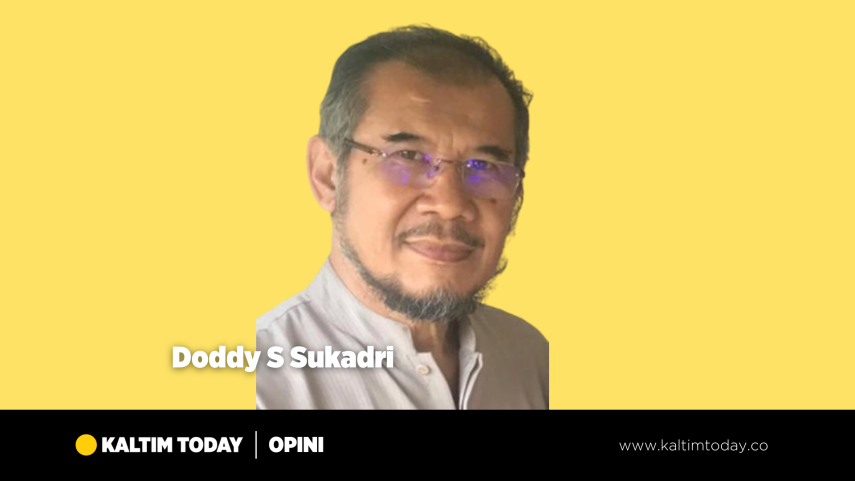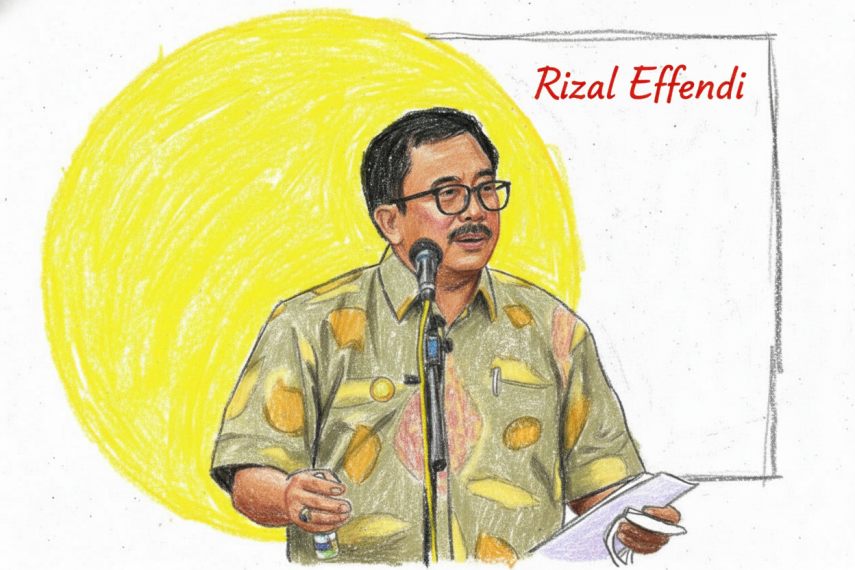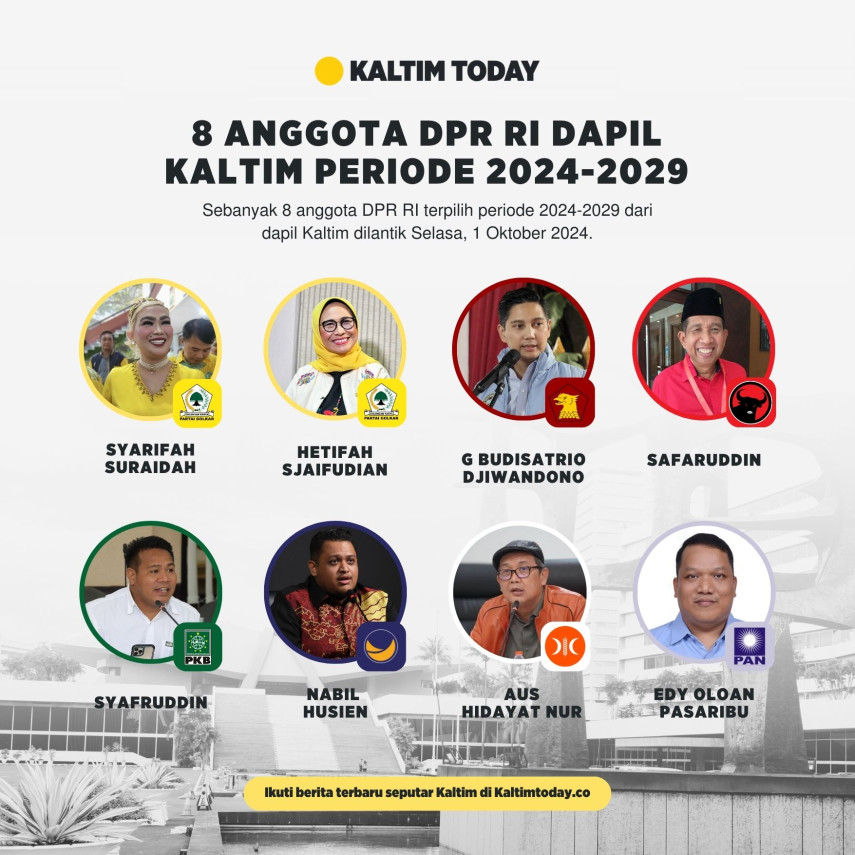Opini
Anak Tak Butuh Busur Patah

Oleh: Ida Farida (Dosen UINSI Samarinda, Ketua Muslimat NU Kota Samarinda)
Anak-anak, kata Khalil Gibran, adalah panah kehidupan yang melesat ke masa depan, sedang kita hanyalah busur yang menegangkan arah. Tapi di negeri ini, busur-busur itu sering rapuh—oleh kekerasan struktural, pengasuhan yang tak sadar, dan sistem sosial yang mengerdilkan imajinasi anak. Maka panah pun sering meleset. Bukan karena salah arah, tapi karena busurnya patah sebelum sempat menegakkan daya.
Setiap tahun, kita rayakan Hari Anak dengan gegap gempita dan jargon yang megah: anak sebagai harapan bangsa, penerus masa depan, dan pewaris peradaban. Tapi apakah semua itu benar-benar tercermin dalam cara kita mengasuh dan melindungi mereka? Atau justru kita menjadikan mereka korban ambisi yang belum tuntas, trauma yang belum sembuh, dan sistem yang belum berpihak?
Anak sering kali dibentuk untuk memenuhi ekspektasi—bukan dikembangkan sesuai potensinya. Sekolah menilai mereka lewat angka, keluarga menilai mereka lewat prestasi, masyarakat menilai mereka lewat kepatuhan. Sedikit sekali yang benar-benar mendengarkan suara anak sebagai subjek, bukan objek dari proyek bernama "sukses". Mereka didesak tumbuh cepat, tapi tak diberi ruang untuk bermain dan bertanya. Mereka dituntut menjadi hebat, tapi tak diberi hak untuk lemah.
Dalam kajian perkembangan manusia, seperti yang dijelaskan oleh Urie Bronfenbrenner, anak tumbuh dalam ekosistem berlapis: mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga kebijakan negara. Maka, tanggung jawab pengasuhan tak bisa dibebankan hanya pada rumah tangga, apalagi individu ibu. Ia adalah tugas kolektif yang menuntut keberpihakan sistemik. Negara seharusnya tidak hanya merumuskan regulasi, tetapi juga menjamin pelaksanaan: dari cuti orang tua yang layak, layanan kesehatan anak yang merata, hingga pendidikan yang mengutamakan rasa aman dan tumbuhnya rasa ingin tahu.
Perspektif keislaman pun memberi dasar normatif yang kuat. Dalam Islam, anak adalah amanah (titipan), bukan properti. Al-Qur’an menyebut mereka sebagai zinat al‑hayat al‑dunya (perhiasan dunia), sekaligus fitnah (ujian)—menandakan bahwa anak adalah pusat tanggung jawab moral dan sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah,” artinya anak hadir dalam kesucian potensial yang hanya bisa berkembang jika dipelihara dengan kasih dan keteladanan. Pemikir seperti Imam al‑Ghazali menekankan pentingnya pendidikan yang lembut, bertahap, dan membebaskan. Namun dalam praktiknya, pola pengasuhan kita sering masih didominasi oleh kontrol, paksaan, bahkan kekerasan atas nama disiplin dan agama.
Dari perspektif sosiologis, seperti yang dijelaskan Emile Durkheim, anak bukan sekadar individu biologis, melainkan entitas sosial yang dibentuk—dan membentuk—masyarakat. Pengasuhan yang gagal memanusiakan anak akan menghasilkan generasi yang resisten, apatis, atau bahkan destruktif terhadap struktur sosial itu sendiri. Keberpihakan pada anak bukan urusan belas kasih, melainkan strategi stabilitas sosial jangka panjang.
Ironisnya, dalam banyak kebijakan, anak masih ditempatkan dalam posisi pasif. Mereka jarang dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut hidup mereka. Padahal Konvensi Hak Anak PBB telah menegaskan pentingnya partisipasi anak sebagai prinsip dasar—selain perlindungan, kelangsungan hidup, dan nondiskriminasi. Memberi suara kepada anak dalam kebijakan pendidikan, layanan publik, hingga tata kota bukan romantisme, tetapi bentuk kesadaran bahwa masa depan tidak bisa dibangun tanpa mendengar mereka yang akan menjalaninya.
Di tengah berbagai perubahan sosial—digitalisasi, urbanisasi, dan krisis iklim—tantangan dihadapi anak-anak semakin kompleks. Mereka tidak hanya menghadapi tekanan dari rumah dan sekolah, tetapi juga dari dunia virtual yang semakin tak terkendali. Tanpa literasi digital memadai dan pengawasan etis dari institusi, mereka tumbuh dalam ruang yang penuh kebisingan tapi minim bimbingan. Dalam konteks ini, busur pengasuhan tak cukup hanya hadir di rumah; ia harus diperkuat oleh kebijakan publik, teknologi etis, dan ekosistem sosial yang peduli.
Negara-negara maju seperti Finlandia, Norwegia, atau Islandia menunjukkan bahwa keberpihakan pada anak dijalankan secara terstruktur: kurikulum edukatif yang membebaskan, dukungan kesejahteraan keluarga, pelibatan anak dalam kebijakan mereka. Negara tidak menunggu “sukses” untuk peduli, mereka bersikap proaktif sejak awal. Kontras dengan kita, di mana perkawinan anak masih marak, kekerasan institusional belum tertangani tuntas, dan ruang aman anak di dunia digital minim perlindungan.
Lebih dari itu, penting untuk menata ulang paradigma pembangunan: dari melihat anak sebagai objek investasi masa depan menjadi melihat mereka sebagai warga negara penuh hak sekarang juga. Menunda tanggung jawab atas nama ekonomi atau politik adalah bentuk kekerasan institusional yang sering dimaafkan.
Anak-anak tak butuh seremoni tahunan. Mereka butuh jaminan harian bahwa dunia ini layak dihuni oleh tubuh kecil dan pikirannya yang penasaran. Mereka butuh didengar saat cemas, dimengerti saat gagal, dicintai saat tak sesuai ekspektasi. Gibran benar: anak-anak bukan milik kita. Dan tugas kita sebagai busur bukan mengontrol panah, tetapi memastikan busur cukup kuat, lentur, dan jujur untuk melepaskan mereka ke dunia yang lebih baik.
Karena pada akhirnya, anak tak butuh busur patah—mereka butuh kita pulih dulu, agar mereka bisa melesat bebas.
Related Posts
- Tema dan 3 Makna Logo Hari Anak Nasional 2024
- DPRD Berau Minta Pemerintah Kawal Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur
- Peringati Hari Anak Nasional, OJK dan bank bjb Gelar Kampanye Ayo Menabung di Bogor
- Komitmen Turunkan Angka Kematian Bayi, Kemenkes Upayakan Pemasangan Alat USG di 10.000 Puskesmas
- Sambut Hari Anak Nasional, Andi Harun Tekankan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Usia Dini