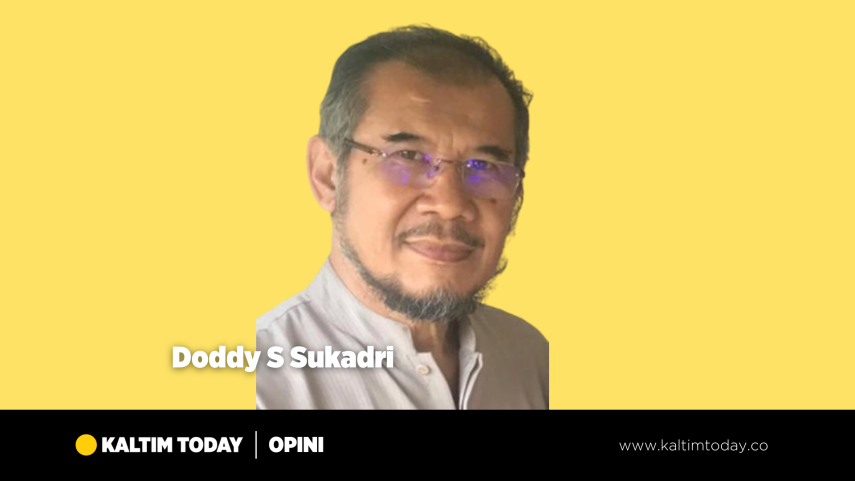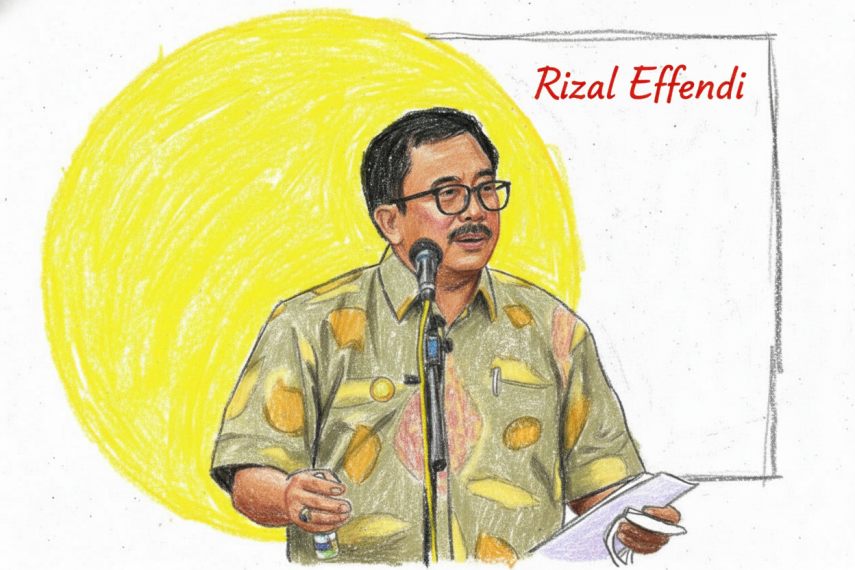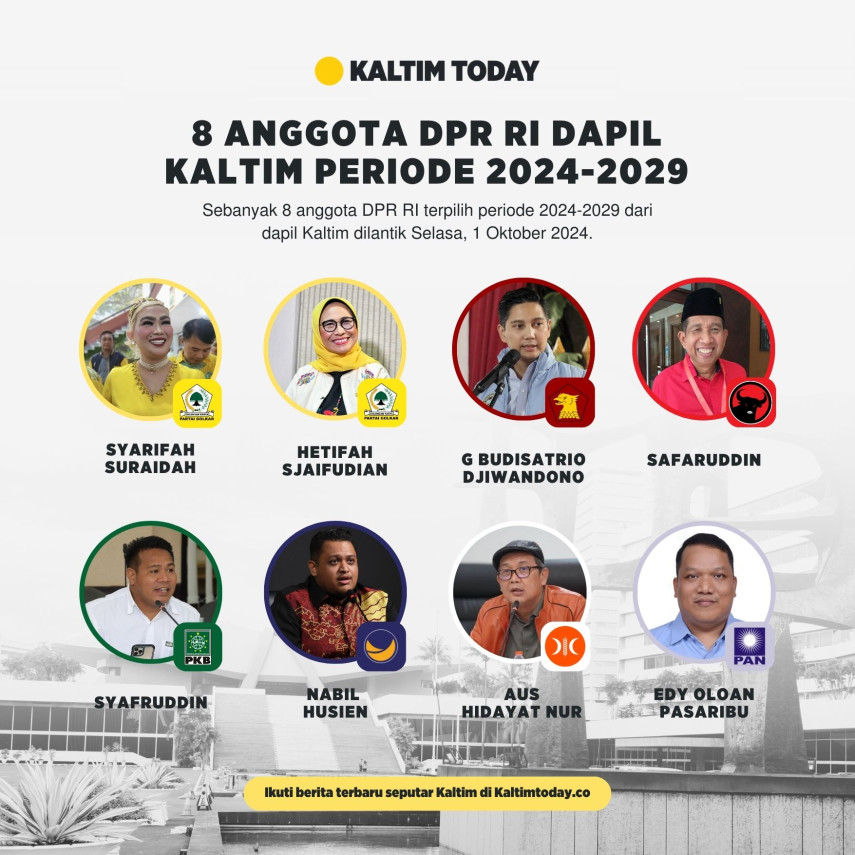Opini
Rebranding Projo dan Pelajaran Transformasi Identitas Politik

Oleh: Andi Muhammad Abdi, Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UINSI Samarinda
REBRANDING suatu organisasi bukan sekadar mengganti logo atau slogan. Ia adalah upaya mengubah makna simbolik, menata persepsi publik, dan menegosiasikan ulang posisi organisasi tersebut dalam suatu dinamika tertentu. Inilah yang kini dilakukan Projo, organisasi relawan yang sejak awal kehadirannya identik dengan figur mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam Kongres III digelar pada 1-2 November 2025, Projo memutuskan mengganti logo lama bergambar wajah Jokowi dan menegaskan bahwa Projo bukan akronim dari Pro Jokowi, melainkan serapan dari bahasa Sanskerta yang bearti “Negeri”, dan dalam bahasa Kawi berarti “Rakyat”. Sebuah pernyataan yang mengundang tafsir, kritik, dan pertanyaan, apakah ini tanda pergeseran orientasi politik atau strategi komunikasi untuk memperpanjang relevansi organisasi di era pasca-Jokowi?
Secara konseptual, rebranding dalam teori komunikasi adalah proses reposisi makna, yaitu upaya menggeser citra lama menuju identitas baru tanpa kehilangan legitimasi publik. Menurut Stuart Hall, makna sosial tidak pernah tetap. Ia selalu dinegosiasikan melalui wacana dan simbol. Sebab itu, ketika Projo mengganti logonya dan menegaskan makna Projo sebagai kata dari bahasa Kawi dan Sanskerta yang berarti rakyat atau negeri, sesungguhnya ia sedang melakukan negosiasi ulang atas identitasnya. Dari gerakan relawan yang berporos pada figur menjadi gerakan yang berpusat pada rakyat.
Namun proses rebranding bukanlah hal mudah, terutama bagi organisasi yang lahir dari semangat personalistik. Dalam politik Indonesia, relawan kerap melekat pada figur pemimpin, bukan pada gagasan. Projo adalah contoh paling kuat dari fenomena personal branding politics. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, Projo menjadi simbol loyalitas politik yang militan. Nama, logo, dan kegiatan organisasi semuanya diasosiasikan dengan personal Jokowi. Karena itu, ketika Projo kini bukan lagi Pro Jokowi, publik wajar mempertanyakan apakah mungkin organisasi relawan bisa sepenuhnya menanggalkan figur yang menjadi sumber legitimasinya?
Dari kacamata komunikasi politik, langkah ini menunjukkan kesadaran strategis. Projo sedang membangun narasi transisi dan transisi narasi. Mencoba bertahan di ruang publik yang pasca 2024 tak lagi diisi oleh pesona Jokowi. Rebranding adalah bahasa komunikasi baru. Pesan simbolik bahwa mereka siap beradaptasi dengan ekosistem kekuasaan yang berubah. Dengan mengedepankan makna “rakyat”, Projo berupaya menegaskan kembali eksistensi keberpihakan pada kepentingan publik, bukan individu.
Di sinilah pentingnya teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer yang menegaskan bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi, bukan ditentukan secara tunggal oleh pencipta simbol. Artinya, walaupun Projo berupaya menanamkan makna baru pada logonya, makna itu akan tetap bergantung pada bagaimana publik menafsirkannya. Jika publik masih melihat Projo sebagai perpanjangan tangan Jokowi maka upaya rebranding hanya menjadi ritual kosmetik, bukan transformasi ideologis.
Rebranding Projo juga bisa dibaca sebagai bentuk strategi komunikasi untuk menjaga jarak simbolik dengan tokoh lama tanpa memutus hubungan emosional. Dalam banyak kasus, organisasi politik melakukan hal ini untuk memperluas basis dukungan dan kemungkinan menjalin relasi dengan sekutu baru. Dalam konteks politik Indonesia yang cair, langkah ini terbilang taktis. Ia menjaga keseimbangan antara loyalitas masa lalu dan fleksibilitas masa depan. Namun di sisi lain, strategi ini juga menyimpan resiko kehilangan kepercayaan basis akar rumput yang dulu bergabung karena figur Jokowi.
Rebranding Projo adalah ujian terhadap kemampuan mereka mengelola narasi publik. Terutama pada cara mereka menyampaikan pesan baru agar tidak dianggap sekadar oportunistik. Termasuk bagaimana membangun kohesi internal ketika identitas lama diganti. Dalam teori framing, proses komunikasi publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai realitas agar diterima sesuai tujuan. Maka, keberhasilan rebranding Projo bergantung pada efektifitas mereka membingkai ulang dirinya dari pendukung Jokowi menjadi gerakan rakyat.
Namun, membingkai “rakyat” bukan hal sederhana. Jika Projo tidak menawarkan narasi substantif tentang apa yang dimaksud “rakyat” dalam konteks perjuangannya, maka rebranding ini berisiko jatuh menjadi slogan kosong. Di era komunikasi digital, publik cepat mengenali ketidaktulusan simbolik. Media sosial tidak hanya menjadi alat promosi, tapi juga sebagai ruang validasi.
Dalam konteks ini, Projo harus menunjukkan perubahan bukan hanya di permukaan, tetapi juga dalam substansi gerakannya. Jika mereka benar-benar ingin menegaskan diri sebagai gerakan rakyat, maka orientasi komunikasinya harus berubah dari komunikasi top down menjadi partisipatif. Dari mobilisasi elektoral menjadi edukasi politik. Dari sekadar mendukung kekuasaan menjadi mengawal kebijakan. Rebranding yang ideal tidak berhenti di logo, tetapi berlanjut dalam praktik komunikasi yang membangun kepercayaan publik.
Langkah ini juga mencerminkan evolusi pola komunikasi politik di Indonesia. Kita sedang menyaksikan bagaimana organisasi relawan berusaha keluar dari bayang-bayang personalisasi politik menuju institusionalisasi gerakan. Hal ini merupakan upaya untuk kembali ke ruang publik rasional, di mana wacana politik tidak lagi didominasi oleh figur, melainkan oleh argumentasi dan kepentingan kolektif. Bila Projo berhasil menempuh jalan ini, maka mereka bukan sekadar berubah nama, melainkan berkontribusi dalam memperkuat demokrasi deliberatif di Indonesia.
Namun, tantangan terbesarnya tetap pada kejujuran komunikasi. Publik kini lebih kritis, skeptis terhadap simbol, dan menuntut konsistensi antara ucapan dan tindakan. Rebranding hanya akan berhasil bila diikuti oleh perubahan perilaku organisasi, terutama pada cara mereka berbicara di publik, berinteraksi dengan masyarakat, dan bersikap terhadap kekuasaan. Bila tidak, maka rebranding hanya akan menjadi gimmick semata.
Pada akhirnya, rebranding Projo harus dibaca bukan sekadar sebagai peristiwa organisasi, tetapi sebagai cermin transformasi komunikasi politik di era pasca figur. Ini menunjukkan bahwa dalam politik modern, simbol dan makna adalah arena pertarungan yang sama pentingnya dengan suara dan kekuasaan. Dalam dunia yang makin sadar citra, mengubah makna adalah bentuk baru dari perjuangan politik itusendiri. (*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co
Related Posts
- Surat Terbuka untuk Andi Harun: Membangun Peradaban Lewat Perpustakaan
- Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Seno Aji Akui Biaya Pilkada Langsung Lebih Besar
- Dosen Unmul Kritik Pilkada Lewat DPRD, Sebut Potensi Hidupkan Kembali Orde Baru
- Pemulihan Pasca Bencana Banjir, Kaltim Kirim Bantuan Rp 1 Miliar ke Sumatera Barat
- Komisi III DPR: Pendemo Hanya Bisa Dipidana Jika Picu Keonaran dalam KUHP Baru