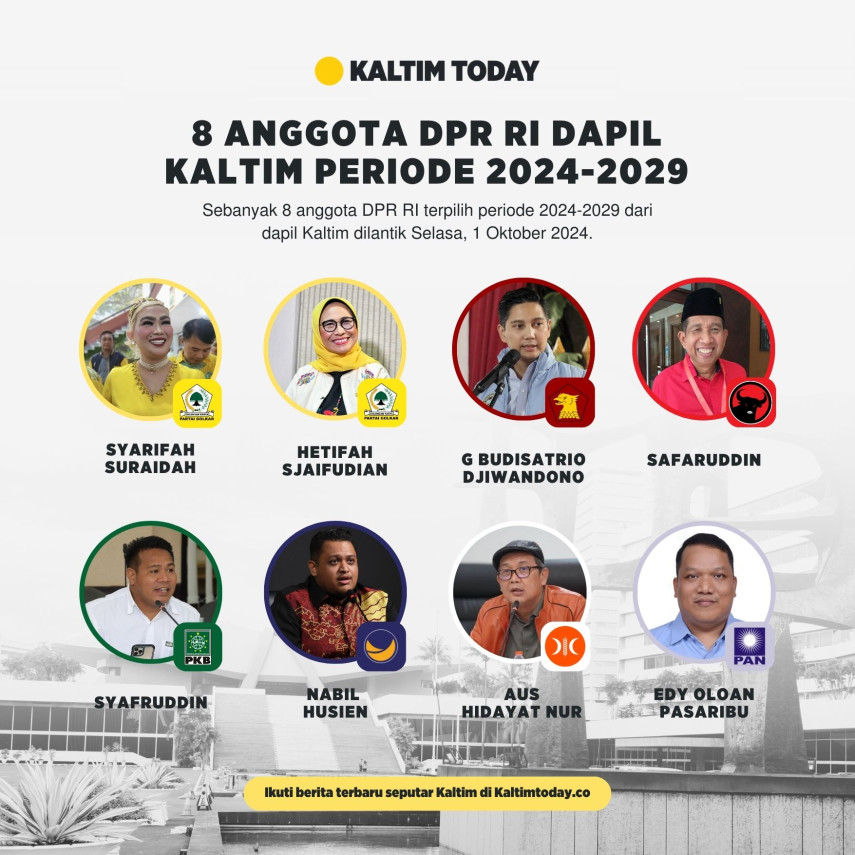Lipsus
Ironi Ketimpangan Energi di Kutai Timur: Kaya Batu Bara, Miskin Penerangan, Proyek Hijau Dikorupsi

Di sebuah desa pesisir Kutai Timur, deru mesin genset menjadi penanda malam. Saat petang tiba, warga bergegas memanfaatkan lima jam listrik yang mereka punya, sebelum gelap kembali menguasai rumah dan jalanan. Ironinya, desa itu terletak di jantung tambang batu bara, sumber energi yang menyalakan kota-kota besar di negeri ini. Namun bagi warga Mandu Pantai Sejahtera, listrik 24 jam masih jadi kemewahan yang ditunggu saban hari.
SEMBURAT jingga berpadu awan pekat menggantung di langit. Petang nyaris tiba di Desa Mandu Pantai Sejahtera, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Muhidin (43), yang kala itu membonceng sang istri, Harlina (46), buru-buru memacu motor skutiknya agar tak terjebak malam. Melewati kebun sawit dan beberapa rumah warga yang posisinya jarang-jarang, motornya meliuk menghindari lubang yang sesekali menganga di jalan belum teraspal.
"Coba perhatikan itu, ada tiang tapi terpasang begitu saja. Tidak ada apa-apanya (jaringan listrik)," kata Muhidin, yang tiba-tiba menepi untuk memperlihatkan deretan tiang yang berbaris nyaris sepanjang jalan. Usai menunjukkan tiang dari kayu ulin itu, dia kembali melanjutkan perjalanan.
Setibanya di rumah, waktu nyaris menunjukkan pukul 18.00 Wita. Pasangan suami istri itu segera berbagi tugas. Muhidin membersihkan ikan di halaman belakang. Harlina, memasak nasi sembari menyiapkan bumbu di dapur.
"Derrum-derrummm!”
Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar deru bak mesin kapal. Suaranya cukup memekakkan telinga. Belakangan baru saya tahu, suara itu rupanya berasal dari generator set (genset) komunal yang diletakkan di sebuah bangunan kayu semi permanen ukuran sekitar 7x5 meter di dekat kantor Desa Mandu Pantai Sejahtera. Ia berjarak sekitar 50 meter dari kediaman Muhidin dan Harlina.
"Kalau sudah ada suara kayak mesin kapal, berarti nyala sudah listrik," jelas Harlina. Dia lantas berdiri dari lantai dapur dan bergegas ke kamar.
"Harus buru-buru kita ini, tidak bisa santai. Habis cuci, saya mau keringkan nasi di rice cooker Tidak bisa dikerjakan sekalian nyuci (di mesin) dan masak (di rice cooker). Tidak sanggup listriknya, langsung terketek (padam)," katanya sembari memasukkan setumpuk pakaian kotor ke dalam mesin cuci berdaya 350 watt.
Harlina dan Muhidin adalah warga Desa Mandu Pantai Sejahtera-- atau warga menyebutnya dengan nama Mandu PS. Sudah tiga bulan mereka tinggal di desa ini. Sebelumnya, Harlina yang aslinya berasal dari Desa Kolek-- sebuah desa yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Desa Mandu PS-- tinggal di Desa Mandu Dalam. Sementara Muhidin, adalah putra asli Mandu Dalam. Desa Mandu Dalam sendiri merupakan desa lain yang juga berada di Kecamatan Sangkulirang.
Di Desa Mandu PS, listrik tak tersedia 24 jam. Tapi hanya lima jam sehari. Mulai pukul 6 petang hingga 11 malam. Listrik itu berasal dari genset komunal yang dikelola warga. Kendati begitu, pengelolaannya dalam pengawasan pemerintah desa. Sebab, genset yang dibeli 10 tahun silam itu bersumber dari dana desa.

Di Mandu PS, listrik bukan hanya soal nyala-mati, tapi juga soal daya yang terbatas. Tiap rumah hanya dijatah antara dua hingga empat ampere. Semakin besar kapasitasnya, semakin tinggi pula biayanya. Untuk dua amper--daya paling kecil yang bisa dipasang-- warga mesti membayar antara Rp140 ribu hingga Rp280 ribu per bulan. Kalau ingin menarik empat ampere, tarifnya melonjak dua kali lipat, sekitar Rp370 ribu. Tak heran, sebagian besar warga memilih bertahan di dua ampere saja.
Sejak Juni 2025, tarif listrik di Mandu PS dipatok Rp185 ribu per bulan. Angka itu terbilang lebih ringan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meski nilainya tetap bisa berubah mengikuti harga bahan bakar. Iuran tersebut digunakan untuk membeli solar, biaya perawatan, dan upah operator. Satu unit genset berkapasitas 165 KVA di sana menghabiskan sekitar 120 liter solar hanya untuk beroperasi selama lima jam.
Sebagai perbandingan, seorang warga di Bontang bernama Yulia, hanya membayar Rp400 ribu per bulannya untuk listrik PLN. Dengan kapasitas listrik rumah mencapai 1.200 watt, dia bisa memakai itu untuk dua unit pendingin ruangan (AC) masing-masing berkapasitas setengah PK, dua unit komputer, satu kulkas, enam bohlam lampu, dan mengisi daya baterai ponsel harian. Listrik ini bisa dinikmati 24 jam.
Sementara warga Desa Mandu PS, dengan listrik kapasitas dua ampere itu, hanya bisa menyalakan satu perangkat elektronik tegangan tinggi dan beberapa lampu penerangan rumah. Misanya, satu kulkas dan dua balon lampu. Tak bisa disambi dengan elektronik besar lainnya karena bila dipaksakan, kWh meter atau alat pengukur energi listrik di rumah seketika padam. Atau orang-orang di Mandu PS menyebutnya dengan "listriknya terketek"-- istilah lokal untuk menyebut listrik yang tiba-tiba padam.
Harlina mengatakan, kondisi inilah yang membuat kehidupan di desa ini terasa seperti berjalan di tempat dan terhambat. Terlebih bagi perempuan seperti dia, yang punya beban ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Ada tanggungan "lelah" yang juga berlapis.
Ibu dengan empat orang anak ini bilang, sebagian besar warga yang tinggal di Desa Mandu PS, baik perempuan atau laki-laki, menggantungkan hidup dari sawit. Ada yang bekerja untuk perusahaan swasta, seperti PT Sumber Kharisma Persada, sebuah perusahaan di bawah naungan Astra International. Ada yang mengelola kebun sawit sendiri. Untuk Harlina, dia dan suami mengelola kebun sawit sendiri.
Nyaris saban hari, dia bersama Muhidin pergi ke kebun. Di sana, pekerjaan mereka tak jauh beda: sama-sama merawat kebun, menuai pupuk, bahkan sampai memanen kelapa sawit yang berat tandan buah segar (TBS) bisa mencapai 35 kilogram.
Namun, pekerjaan di kebun hanyalah separuh dari rutinitasnya. Begitu pulang, Harlina masih harus mengerjakan sebagian besar kerja domestik seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiadaan listrik membuat semua pekerjaan itu jadi berat dan tidak efisien. Misalnya, blender untuk meringankan proses memasak.
Persoalan tak berhenti di situ. Keterbatasan daya listrik juga membuat durasi kerja domestik semakin panjang. Biasanya, sepulang dari kebun, Harlina mesti memasak nasi di kompor lalu mengeringkannya di pemanas nasi. Baru setelah nasi matang sempurna, ia bisa menyalakan mesin cuci--karena listrik tak cukup jika keduanya dijalankan bersamaan. Konsekuensi dari kerja panjang itu, waktu istirahatnya kian tergerus.
"Coba kalau ada listrik. Bisa sekalian mencuci dan masak. Kalau kondisinya begini, semua harus satu-satu dikerja. Sudah capek di kebun, capek juga di rumah. Double dikerja, lambat saya istirahat," keluhnya.
Suami Harlina, Muhidin menambahkan, sejatinya mereka berusaha menambah pasokan listrik di rumah melalui energi terbarukan berbasis solar cell. Perangkat itu mereka beli pada 2020 lalu seharga Rp2,7 juta; Rp1,5 juta untuk panel, Rp1,2 juta untuk aki. Ia berkapasitas 50 watt peak (Wp). Namun kapasitas itu hanya cukup untuk lampu penerangan dan mengisi daya baterai ponsel. Tidak sanggup untuk perangkat elektronik bertegangan tinggi.
Kapasitas solar cell ini pun terus menurun seiring tahun. Bila bertahan dengan kondisi baterai seadanya, artinya kapasitas energi dari matahari yang bisa disimpan juga sekadarnya. Karena itu, mereka memilih mengganti baterai itu setiap tahun sekali dengan banderol Rp1,5 juta.

"Hitungannya, dua kali kami membayar ini. Listrik desa iya, solar cell juga. Bisa sampai Rp350-Rp400 ribu (per bulan) kami bayar. Padahal kalau pakai listrik PLN tidak akan sebesar itu, tersedia 24 jam lagi. Itu baru listrik, belum kebutuhan lain," sesal Muhidin.
Listrik Terbatas, Ongkos Hidup Membengkak

Cerita lain juga datang dari Ketua RT 01 Desa Mandu PS, Abu Bakar. Pria yang lahir dan tumbuh di desa ini bercerita, keterbatasan listrik salah satunya berdampak besar pada pendidikan anak-anak. Karena listrik tak ada, warga tak bisa memiliki komputer dan memasang jaringan nirkabel (wireless fidelity/Wifi). Padahal keduanya penting untuk mendukung proses belajar yang belakangan dituntut serba digital oleh negara.
Salah satu momen paling diingat Abu Bakar ketika salah seorang anaknya yang mesti menggunakan laptop untuk belajar. Dia mesti menyediakan genset agar laptop itu bisa diisi dayanya pada siang hari. Ini terjadi ketika pembelajaran dilakukan secara hybrid di masa pandemi Covid-19. Dan untuk menyalakan genset durasi tiga hingga empat jam, dia mesti mengeluarkan uang sekitar Rp25.000.
Abu Bakar menegaskan, ketiadaan listrik ini benar-benar membatasi kualitas hidup warga, membuat ongkos hidup mereka lebih mahal ketimbang warga lain yang memiliki sambungan listrik 24 jam. Dari satu sisi saja, pendidikan, menggandakan pengeluaran keluarga: bahan bakar untuk menyalakan genset dan kuota internet yang secara hitung-hitungan lebih mahal ketimbang berlangganan WiFi bulanan.
"Mau diapa, kondisinya sudah begini," kata Abu, ada nada lirih dalam suaranya. "Makanya kami selalu bilang ke pemerintah, kampung kami itu, Mandu, yang dibutuhkan cuma dua, listrik dan air. Kalau itu sudah,tidak banyak lagi yang masyarakat minta."
Bagi Abu, listrik merupakan kebutuhan yang menyentuh nyaris seluruh aspek kehidupan warga "Susah sekali kalau tidak ada listrik, karena semuanya pakai listrik. Sedot air, masak, belajar anak-anak, sampai orang nikahan pun butuh listrik semua. Tapi kami di sini tidak punya."
Lebih jauh dia menjelaskan, listrik dari genset komunal yang disediakan desa selain terbatas waktu, daya, dan mahal, juga memiliki kendala lain: sering bermasalah. Sepanjang September 2025 saja, sudah dua kali genset rusak. Praktis, ini membuat warga benar-benar menggantungkan energi dari genset pribadi atau solar cell yang kapasitasnya hanya cukup untuk lampu penerangan rumah.
Pada Maret-April 2024 lalu, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kondisinya bahkan lebih buruk: genset mati sebulan penuh. Abu mengingat betul di momen itu, terjadi ketegangan antara warga dan pengurus desa. Dalam satu pertemuan yang dihelat di Balai Pertemuan, warga dan perangkat desa nyaris baku hantam karena tak ada solusi akan kondisi mereka.
"Panas sekali itu," kenangnya. "Sampai tentara dan polisi turun supaya tidak kelahi." Belakangan baru diketahui, genset tak berfungsi karena jaringan kabelnya tersambar petir, yang berdampak ke sensor oli dan panel. Ini menurut penuturan Kepala Desa Mandu PS, Hendra.
Listrik desa yang padam sebulan penuh membuat kehidupan warga makin susah. Saban pagi hingga malam, deru mesin genset rumahan bersahutan di sepanjang jalan desa. "Tidak karuan lagi. Sepanjangan nyala genset semua, sudah kayak bunyi kumbang bhunggg, bhungggg, karena masing-maisng itu," kata Abu meniru suara bising yang kala itu akrab di telinganya.
Pada masa Pilkada 2024 lalu, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman-- yang kembali terpilih untuk kedua kalinya-- menjanjikan secercah harapan. Listrik PLN direncanakan masuk ke Desa Mandu PS setidaknya pada 2026. Abu menaruh harapan besar dari janji itu. Dia berharap, bupati merealisasikan janjinya, bukan sekadar ucapan kampanye yang menguap setelah pemilihan. Warga, termasuk Abu, sudah lelah menunggu.
Kondisi memprihatinkan ini pun diam-diam menghadirkan perasaan tak adil dalam hati Abu. Sebab, kampung di seberang mereka, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, yang hanya dibatasi perjalanan membelah muara sungai sekitar 21 menit, sudah menikmati listrik 24 jam. Sementara Desa Mandu PS, dan 8 desa tetangganya, sejak dulu harus bertahan dengan segala keterbatasan.
“Kalau dibilang merasa tidak adil, yah sebenarnya begitu. Kami ini seperti terisolir sementara di seberang, semua [listrik] sudah merata,” tandasnya.
Lapis Ironi Keterbatasan Listrik di Kutim: Dikepung Batu Bara Hingga PLTS Dikorupsi
KONDISI yang dialami Harlina, Muhidin, Abu Bakar, atau 761 warga Desa Mandu PS lainnya bukan sekadar malam yang terasa datang lebih cepat di kampung mereka. Namun ada persolan lain: ketimpangan energi. Kondisi ini makin mengenaskan sebab bila melihat lokasi Desa Mandu PS, sejatinya ia terletak di salah satu "jantung" produsen batu bara terbesar di Kaltim, yakni Kutai Timur. Daerah yang dengan bangga menyebut dirinya sebagai "Magic Land" ini merupakan produsen batu bara terbesar kedua di Kaltim setelah Kutai Kartanegara (Kukar).
Secara geografis, sebetulnya Desa Mandu PS tak jauh-jauh amat dari perusahaan tambang batu bara terdekat. PT Indexim Coalindo, misalnya. Perusahaan pemegang konsesi seluas 24.050 hektar ini berjarak hanya sekitar 32 kilometer bila menyebrang laut dari Desa Benua Baru Ilir, Sangkulirang. Sementara bila mengambil rute memutar melalui Desa Sempayau dan Desa Pelawan, jaranya sekiar 70 kilometer. Atau misalnya perusahaan seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC)-- anak usaha PT Bumi Resources (BUMI)-- dari site Bengalon, jaraknya sekitar 90 kilometer.
Saban hari, perusahaan tambang itu mengeruk batu bara dari perut bumi Kutai Timur. Ia lantas dikirim ke berebagai negara seperti China, India, Malaysia, Filipina dan Hong Kong. Di dalam negeri, ia digunakan untuk menerangi gedung pencakar langit di Jakarta, mega pabrik, hingga menjaga listrik tetap menyala di rumah-rumah warga dari Sumatera hingga Papua. Ini tidak mengherankan, sebab 67 persen pembangkit listrik yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya.
Pada 2024 saja, PLN menggunakan 131 juta ton batu bara untuk pembangkit listriknya. Angka ini menegaskan bahwa batu bara masih menjadi pondasi utama dalam bauran energi Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik domesti.
Namun ironisnya, di tengah limpahan sumber daya itu, sebagian wilayah penghasil batu bara ini justru masih tenggelam dalam gelap. Di Jakarta, listrik padam dua jam saja sudah menimbulkan kegaduhan. Sementara di Desa Mandu PS, warga bahkan tak pernah merasakan listrik 24 jam sejak dahulu.
Kondisi ini sebetulnya bukan hanya dirasakan oleh Mandu PS, tapi 8 desa tetangganya. Seperti Desa Tanjung Manis, Mandu Dalam, Pelawan dan Saka yang biasa disebut "Sangkulirang seberang" karena letaknya di muara sungai. Kesemua desa ini mempunyai satu kesamaan: hidup dalam keterbelakangan akibat keterbatasan listrik.
Hingga September 2025, dari 141 desa di Kutim, 26 di antaranya belum mendapat pasokan listrik PLN. Dalam periode yang sama, cakupan elektrifikasi di Kutim baru di angka 89,7 persen atau setara dengan 114.579 jumlah pelanggan. Dengan kapasitas tersambung (KW) mencapai 306.176.900. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Kutim mendapat listrik pada 2027.
Ketika Energi Bersih Jadi Ladang Kotor
Pada 2017, Pemkab Kutim sejatinya coba menghadirkan solusi praktis: menghadirkan PLTS Home System. PLTS itu rencananya digunakan sebagai alat untuk memenuhi energi bagi rumah-rumah, sekolah, puskesmas, hingga rumah ibadah di desa yang belum mendapat pasokan listrik PLN. Pemkab mesti mengambil langkah cepat untuk mendorong elektrifikasi di Kutim yang kala itu masih di angka 60 persen. Pemkab menilai, bila menunggu PLN, sulit mendorong akselerasi elektrifikasi. Ini sebagaimana disampaikan Sekretaris DPM-PTSP Kutim, Muhammad Yani, ketika ditemui di kantornya, Komplek Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Kutai Timur, akhir September 2025.
"Tujuannya sebenarnya baik, karena berdasar data elektrifikasi baru 60 persen saat itu untuk PLN, Saat itu 2017, harus ditambah dengan PLTS. Ini juga untuk mendukung visi bupati saat itu, "Kutim Terang," jelasnya.
Proyek ini kemudian dijalankan melalui DPM-PTSP Kutim pada 2020. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp94 miliar. Nilai yang terbilang fantastis untuk ukuran proyek energi di tingkat kabupaten. Namun belum genap setahun setelah proyek bergulir, aroma tak sedap mulai tercium. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim mencurigai adanya praktik korupsi dalam pelaksanaannya.
Menurut Muhammad Yani, kecurigaan itu bermula dari laporan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menemukan kejanggalan di lapangan. Mulai dari dugaan mark-up harga yang tidak masuk akal hingga perangkat PLTS Home System yang tak pernah sampai ke desa-desa penerima manfaat.
"Dapat laporan proyek itu dimark-up. Seandainya baik saja, ya tidak ada masalah," kata pria yang kala proyek itu dijalankan, menjabat sebagai Kabid Pengembangan, Energi, SDM dan Promosi DPMPTSP Kutai Timur.
Mantan Kasi Intel Kejari Kutim Yudo Adiananto dalam konferensi persnya di Kutai Timur pada 2022 menjelaskan, pihaknya mulai melakukan pendalaman terhadap kasus ini usai mendapat laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat yang menyebut ada kerugian negara Rp53,6 miliar dari proyek PLTS ini.
Dari kasus ini, kata Yudo, modus dan peran para tersangka berbeda. Mulai dari mark-up, proyek dijadikan penunjukkan langsung (PL) yang dipecah dalam 469 paket senilai Rp200 juta, juga proyek fiktif di mana tersangka mengeluarkan anggaran sedangkan pengerjaan tidak pernah dilakukan.
Dari hasil penyidikan, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya aparatur sipil negara (ASN) DPM-PTSP Kutim, dan seorang lagi direktur perusahaan rekanan. Penetapan tersangka dilakukan pada Desember 2022.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda kala itu menjatuhkan hukuman menjatuhkan hukuman berbeda pada tiap tersangka. Panji Asmara divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 5 bulan; M Zohan Wahyudi divonis 8 tahun penjara denda Rp750 juta subsider 4 bulan; Abdullah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 4 bulan; dan Herru Sugonggo divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp750 subsider 6 bulan.
Kasi Intel Kejari Kutim saat ini, Rahadian Arif Wibowo, enggan berkomentar banyak terkait kasus ini. Alasannya, kasus sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan ketika penyidikan dilakukan, ia belum bertugas di Kutai Timur. Namun berdasarkan informasi yang diterima, proyek itu mestinya disalurkan ke seluruh desa yang belum mendapat pasokan listrik PLN, termasuk Desa Mandu PS.
Pernyataan itu sejalan dengan penuturan Sekretaris DPMPTSP Kutim, Muhammad Yani, yang membenarkan bahwa sasaran proyek memang mencakup semua desa non-elektrifikasi di Kutai Timur.
“Saya kurang tahu detailnya. Tapi setahu saya, itu untuk semua desa yang belum mendapat listrik,” ujar Rahadian saat ditemui di kantornya, Sangatta, Kutim, awal Oktober 2025.
Kondisi ini seolah menempatkan Kutai Timur dalam paradoks yang ironis. Sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, yang notabene tulang punggung utama pembangkit listrik nasional, masih banyak daerahnya tenggelam dalam gelap. Sementara ketika mencoba melalui energi bersih, ternyata ia dijadikan ajang bancakan.
Akibatnya, warga menjadi korban. Di Desa Mandu PS, seluruh narasumber yang saya temui, termasuk kepala desa tak tahu-menahu soal rencana pemasangan PLTS itu. Mereka baru mendengar kabar proyek tersebut ketika saya menanyakannya. Padahal, baik Abu Bakar, Muhidin, maupun Harlina menegaskan, mereka akan sangat menyambut baik bila program itu benar-benar ada dan berfungsi.
Bagi mereka, tak penting listrik itu berasa dari PLTS atau PLN. Yang terpenting, ia mampu menerangi kehidupan warga secara layak, mencukupi kebutuhan harian, dan tak membebani dengan harga mahal.
"Saya baru dengar itu. Padahal bagus saja kalau jalan. Sebenarnya kalau kami, mau PLTS kah, PLN kah, asal bisa 24 jam, kami terima semua," kata Abu Bakar.
Sementara itu, Kepala Desa Mandu PS, Hendra mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi janji bupati untuk menghadirkan listrik pada 2026 mendatang. Namun, karena tak ada yang bisa menjamin apakah janji itu akan diwujudkan, pihaknya mulai menyiapkan langkah lain agar pemenuhan kebutuhan listrik warga bisa segera terealisasi.
Hendra mengatakan, Desa Mandu PS bersama delapan desa yang belum menikmati listrik 24 jam berencana menginisiasi pertemuan dengan PT Sumber Kharisma Persada. Mereka berharap perusahaan, yang memiliki jaringan listrik sendiri, dapat membantu warga sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Ini masih rencana. Tapi kami menunggu dulu realisasi dari janji Pak Bupati,” tandasnya.

Setengah Hati Transisi Energi
HADIR sebagai daerah yang diberkahi kekayaan sumber daya alam mestinya menjadi modal bagi Kutai Timur menapaki arah pembangunan berkelanjutan. Namun hingga kini, nyatanya belum ada tindakan serius yang ditunjukkan pemerintah setempat untuk melangkah ke arah itu. Jangankan membuat peta jalan menuju energi hijau, pemetaan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) pun mereka tak punya.
Di sisi lain, ketimpangan energi masih menganga. Beberapa daerah di Kutai Timur, khususnya di pelosok dan pesisir, masih belum menikmati listrik secara merata. Ketimpangan inilah yang menegaskan bahwa transisi energi di Kutai Timur, masih berjalan setengah hati.
Kepala BRIDA Kutim, Juliansyah secara terbuka mengakui, hingga kini memang belum ada peta jalan atau riset terkait potensi energi baru terbarukan (EBT) yang komprehensif yang pihaknya lakukan. Kurangnya peneliti menjadi alasan mereka kesulitan dan belum memiliki riset yang cukup dalam EBT atau energi hijau.
“Mayoritas periset kami memiliki kepakaran sosial humaniora. Akan tetapi, tahun ini kami telah memiliki satu SDM periset yang memiliki kepakaran sains dan teknologi, sehingga orientasi terkait EBT akan menjadi pertimbangan kami masuk ke dalam rencana induk penelitian kami,” kata Juliansyah kala menjawab pertanyaan tertulis yang diajukan Kaltim Today, awal Oktober 2025.
Dia pun mengakui, sebagai daerah penghasil batu bara, memang ironis ketika masih ada puluhan desa di Kutim belum mendapat pasokan listrik memadai. Pada 2023 lalu, BRIDA telah melakukan riset terkait Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, yang salah satu indikatornya menyoroti akses listrik.
“Memang kami menemukan terdapat beberapa desa masih belum teraliri listrik, khususnya pada Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran,” ujarnya.
Juliansyah menilai, riset dan inovasi hijau sejatinya bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan keterbatasan pasokan listrik, khususnya di daerah pedalaman dan pesisir Kutim. Oleh sebab itu, pihaknya tengah menginisiasi agar riset energi terbarukan bisa dimasukkan dalam rencana Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah dan diselaraskan dengan RPJMD.
"Kalau sudah dimasukkan, maka riset hijau juga bisa dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai," katanya.
Kemudian, terkait proyek PLTS home system yang sempat digagas Pemkab Kutim pada 2020 namun tersandung kasus korupsi. Menurutnya, program semacam itu masih layak dilanjutkan. Namun dengan catatan, diperlukan pengawasan, mekanisme, serta evaluasi yang baik agar pelaksanaan PLTS tersebut tepat sasaran.
Korupsi ini, kata dia, tentu sangat disayangkan. Selain menggerus kepercayaan publik, juga ujungnya publik menjadi korban. Sebab listrik yang mestinya dinikmati, justru tidak ada. "Tentu kami sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Bukan hanya pada dampak sosial, tetapi juga ekonomi masyarakat yang terhambat. Aksesibilitas informasi menjadi lambat sehingga kemajuan SDM masyarakat tertinggal dibandingkan desa yang telah dialiri listrik,” jelasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan, Juliansyah mengusulkan agar Pemkab Kutai Timur membentuk tim transisi energi. Tim itu, katanya, mesti diisi oleh orang-orang kompeten di bidangnya, berpengalaman, dan bukan sekadar penunjukkan.
"Kami menilai perlu dibentuk tim transisi energi berisikan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan, bukan hanya penunjukan secara seremonial,” tegasnya.
Terpisah, Kabag Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kutim, Arif Nur Wahyuni, menjelaskan bahwa pemkab tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam urusan ketenagalistrikan. Hal itu mengacu pada perubahan regulasi yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik sebagian kewenangan ketenagalistrikan ke pemerintah pusat dan provinsi.
“Kalau dulu masih ada di kabupaten lewat UU Nomor 30 Tahun 2009, tapi setelah UU 23/2014 keluar, kewenangan itu sudah tidak ada lagi. Dinas ESDM kabupaten juga sudah ditarik,” ujar Arif Nur Wahyuni ketika ditemui di kantornya, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, awal Oktober 2025.
Kutai Timur, yang memiliki luas wilayah cukup besar dan kondisi geografis beragam, diakui menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses listrik. Jarak antar permukiman yang jauh, keterbatasan sarana pendukung seperti jalan, dan keterbatasan anggaran, menjadi hambatan utama penyaluran jaringan.
“Kadang untuk membawa tiang listrik saja sulit karena akses jalannya terbatas,” katanya.
Selain jaringan PLN, Arif Nur Wahyuni menyebut Pemkab juga mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk daerah yang sulit dijangkau. Walau mendorong penggunaan EBT, namun dia mengakui hingga kini belum ada kajian mendalam dan komprehensif terkati potensi EBT di Kutim. Pemantauan ini biasanya dilakukan lantaran warga desa sudah mendesak akan listrik, tapi jaringan PLN belum bisa menjangkau kampung mereka.
“Listrik, kan, tidak harus dari PLN. Kita juga melihat potensi energi lain sesuai kondisi wilayah. Kalau di sana cocoknya mikrohidro, ya itu yang dikembangkan. Kalau limbah sawit bisa dijadikan biogas, kita koordinasikan agar bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Salah satu contoh penerapan energi alternatif adalah pemanfaatan limbah cair kelapa sawit oleh PT Telen Prima Sawit di Kecamatan Muara Bengkal dan Karangan yang bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan listrik lokal. Skema serupa, kata Arif, bisa dikembangkan di wilayah lain seperti Sandaran, yang memiliki potensi limbah sawit cukup besar.
Pemanfaatan limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) ini memang cukup serius dijajaki Pemkab Kutim. Ini setidaknya terlihat dari sosialisasi yang dilakukan Bagian SDA Kutim pada 6 Mei 2025 lalu yang diikuti pelajar, pemerhati lingkungan, mahasiswa terkait "manfaat" POME sebagai sumber energi yang diklaim "berkelanjutan". Pemkab menyebut POME bisa jadi solusi untuk desa yang belum mendapat layanan dasar kelistrikan. Caranya: Pemkab Kutim memfasilitasi skema kerja sama antara PLN dan perusahaan sawit dengan memanfaatkan kelebihan daya listrik dari limbah cair sawit yang diubah menjadi biogas.
"EBT, kan, banyak. Bisa mikrohidro kayak di Desa Tepian Terap, PLTS komunal di Pulau Miang, bisa juga dari biogas. Biogas ini manfaatkan POME dari sawit," katanya.
Ini juga diperkuat dengan pernyataan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Ketika ditemui di sela-sela kegiatannya awal Oktober 2025 lalu, Ardiansyah Sulaiman bilang akan resmikan listrik di salah satu desa di Kecamatan Sandaran. Listrik itu bersumber dari perusahaan sawit PT Bumi Mas Agro (BMA). Sebanyak 9-15 desa lainnya sepanjang 2025 juga menerima listrik dari sumber yang sama. Diketahui, PT BMA disebut akan menyalurkan sekitar 1 megawatt ke tujuh desa di sekitarnya melalui jaringan interkoneksi.

"Kalau EBT, semua daerah berkomitmen. Kami di Kutim, siap dengan menggunakan biodiesel sawit yang insha Allah akan diresmikan di Kecamatan Sandaran itu. Ini kontribusi perusahaan PT BMA yang punya kelebihan excess power," sebut Ardiansyah Sulaiman.
Hadirnya teknologi untuk mengubah limbah cair sawit jadi sumber energi listrik memang patut diapresiasi. Namun, ia juga perlu dipandang secara kritis. Pemanfaatan ini dikhawatirkan menjadi upaya greenwashing atau menghadirkan citra seolah industri sawit bersih dan hijau. Padahal, ada lusinan hasil kajian yang menunjukkan industri sawit menghadirkan banyak persoalan, utamanya dalam deforestasi dan konflik agraria.
Dalam laporan World Resources Institute berjudul “Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions Areas,” yang terbit 2017 lalu menyebutkan, perkebunan kelapa sawit dan serat kayu, terutama untuk industri pulp dan kertas, merupakan dua penyumbang terbesar hilangnya hutan di Indonesia. Hampir 1,6 juta hektar (4 juta acre) dan 1,5 juta hektar (3,7 juta acre) hutan primer, luas yang lebih luas dari Swiss, masing-masing dikonversi menjadi perkebunan.
Atau misalnya berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), perkebunan sawit merupakan sektor yang paling banyak menyumbang angka konflik agraria di Indonesia. Pada 2023, sedikitnya terjadi 108 letusan konflik agraria di sektor perkebunan dimana 88 kasus disebabkan oleh perkebunan dan industri sawit. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan jumlah konflik sebanyak 99 letusan.
“Selain memicu krisis ekologis, ekspansi pembangunan perkebunan sawit skala besar juga menyebabkan tumpang tindih klaim antara masyarakat dan konsesi perusahaan,” sebut KPA sebagaimana dilansir dalam laman resminya.
Dengan kata lain, baik limbah sawit maupun proyek energi terbarukan sama-sama menunjukkan wajah paradoks transisi energi di Kutai Timur. Di satu sisi, pemerintah mengusung jargon energi bersih; di sisi lain, praktik di lapangan justru menunjukkan kebalikannya.
Terkait PLTS home system yang dikorupsi, Arif Nur Wahyuni enggan berkomentar. “Itu saya no komen. Langsung ke DMPTSP saja,” katanya.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan proyek PLTS itu sejak awal memang tak menjanjikan. Dia bahkan menyebutnya sebagai proyek yang tidak efektif dan "asal-asalan".
"Itu memang tidak efektif, makanya berkasus," katanya. "Jadi, janganlah bikin proyek tanggung-tanggung, proyek-proyek yang asal-asalan."
Mahyunadi bilang, dirinya cenderung lebih cocok bila listrik desa berasal dari PLN. Kalau pun harus berbasis energi terbarukan, seperti PLTS, ia harus komunal. Bukan satu per satu dipasang di rumah warga.
Terkait Kutai Timur menapaki jalan menuju transisi energi, menurutnya Pemkab lebih fokus pada PLN. “Belum, belum ada rencana itu. Kan kita masih fokus penyediaan energi ini dari PLN,” katanya.
Transisi Energi atau Transisi Bancakan? NGO Sebut Korupsi PLTS Kutim Cuma Barang Lama Hadir dalam Bungkus Baru
Koordinator Advokasi ICW, Egi Primayogha mengatakan, bila melihat pola korupsi proyek PLTS Home System yang terjadi di Kutim sejatinya ia hanya "barang lama" yang terbungkus pada hal baru: proyek energi hijau. Korupsi ini, sama saja dengan bancakan yang sudah lalu, ia terjadi karena minimnya transparansi dan tata kelola.
Egi menjelaskan, pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih didominasi PLTU. Namun dalam proses pembangunannya, proyek itu tak jarang berakhir jadi ajang bancakan. Ini setidaknya terlihat dalam pembangunan PLTU Riau-1 atau teranyar, korupsi PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat.
Dari dua contoh kasus kasus ini, korupsi terjadi akibat minimnya transparansi PLN dalam hal perencanaan. Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tak menyebutkan alasan mengapa PLTU itu perlu dibangun atau mengapa ia dibangun di lokasi tertentu.
Kedua, kata Egi, ketiadaan detail nilai kontrak pembangunan. Padahal, ini sangat penting agar publik dapat mengetahui bagaimana negara mendapatkan nilai tertentu untuk pembangunan, berapa yang akan digunakan, dan berapa yang diberi ke swasta. Semuanya ditutupi.
Ketika seruan transisi energi sekarang dimunculkan, yang terjadi adalah tata kelola yang masih bermasalah itu dilanjutkan. Walhasil, proyek pembangkit listrik di luar PLTU kemudian dijadikan bahan bancakan berikutnya. Egi menegaskan bahwa kasus korupsi berbasis energi terbarukan sejatinya bukan barang baru. Ia sudah terjadi jauh sebelum pemerintah "berkomitmen" terhadap transisi energi.
"Bukan hal yang aneh bila tata kelola tidak diperbaiki, transparansi minim, korupsi tetap terjadi. Yang terjadi sekarang, objek bancakannya bergeser dari PLTU ke energi terbarukan," kata Egi ketika berbincang dengan Kaltim Today, Jumat (10/10/2025) malam.
Untuk menghindari potensi bancakan di proyek energi hijau, Egi mengusulkan dua hal. Pertama, keterbukaan informasi. Menurutnya ini sangat penting. Dan keterbukaan ini mesti keseluruhan; mulai perencanaan, pembangunan, dan pertanggungjawaban. Kedua, pengawasan harus diperkuat, baik oleh pemerintah atau aparat penegak hukum (APH).
Pada 2015 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melahirkan inisiatif yang disebut Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Egi menyambut baik inisiatif ini. Cakupan GNPSDA pun cukup luas. Namun sayangnya, gerakan itu tak melahirkan gebrakan atau tindakan yang benar-benar nyata.
"Bagi saya, mengapa tidak baik KPK atau APH membentuk tim khusus untuk mengawasi proyek-proyek transisi energi," usulnya.
Pengkampanye Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian mengatakan, bila berbicara soal PLTS, banyak penelitian menunjukkan bahwa biayanya kini sekitar 15 persen lebih murah dibanding PLTU. Secara prinsip, energi surya justru berpotensi menekan ongkos listrik masyarakat karena sumbernya berlimpah dan tak berbayar. Namun, ketika proyeknya dikorupsi, logika ini menjadi terbalik. Skema mark-up membuat energi yang seharusnya murah justru tampak mahal. Korupsi menutupi fakta bahwa energi surya sejatinya terjangkau. Wahasil, muncul bias di masyarakat bahwa energi terbarukan itu mahal.
Praktik seperti ini justru menimbulkan skeptisisme di masyarakat. Warga yang selama ini hidup tanpa listrik lebih akrab dengan harga solar untuk genset dibanding teknologi PLTS. Ketika proyek energi surya dimark-up, mereka tak punya pembanding untuk menakar kewajaran biayanya. Akibatnya, muncul persepsi bahwa energi surya mahal dan tidak efisien.
“Nanti orang-orang bisa berpikir, ‘ya sudah, pakai fosil saja’, padahal sebenarnya bohong, energi terbarukan terbukti jauh lebih murah,” kata Beyrra ketika berbincang dengan Kaltim Today, Sabtu (10/10/2025).
Menurutnya, bentuk korupsi seperti ini menunjukkan bahwa ekosistem energi terbarukan di Indonesia masih rapuh. Banyak proyek energi hijau dijalankan tanpa membangun sistem keberlanjutan dan tanpa melibatkan masyarakat di tingkat tapak. Ia mencatat, sejumlah proyek pembangkit yang dirancang oleh Kementerian ESDM bahkan tidak bisa bertahan lebih dari dua tahun sejak diresmikan. Biaya pembangunannya besar, tetapi tanpa pelatihan, pemeliharaan, atau transfer pengetahuan ke masyarakat lokal.
“Masalahnya bukan cuma di Indonesia, tapi juga global. Pemerintah kita cenderung hanya fokus pada pengadaan, bukan keberlanjutan. Bahkan di daerah yang dikasih genset saja, pelatihan merawatnya tidak ada,” lanjutnya. Padahal, keberlanjutan bisa dijaga dengan memberi pemahaman dasar kepada masyarakat tentang cara merawat sistem dan mengelola dana perawatan.
Ia menekankan, reformasi struktural mutlak diperlukan. Pemerintah perlu melihat pengelolaan energi terbarukan bukan sekadar instalasi proyek, tetapi membangun sistem yang hidup, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat. Tanpa itu, proyek energi hijau hanya akan jadi ladang bancakan baru.
Terkait tata kelola energi terbarukan di Indonesia, Beyrra menilai ini masih amburadul. Pasalnya, hingga kini belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam praktiknya, berlaku semacam “aturan tak tertulis”. Proyek pembangkit di atas 200 megawatt dikelola pusat, sedangkan di bawah itu menjadi ranah pemerintah daerah. Masalahnya, kewenangan yang terbatas itu tidak diimbangi kejelasan regulasi dan mekanisme pengawasan.
"Nah, berarti, kan, pengelolaan pembangkit energi terbarukan yang diperbolehkan untuk pemerintah daerah itu sebenarnya kapasitas-kapasitas kecil. Tapi regulasinya ini masih tumpang tindih sebenarnya," sebutnya.
Situasi ini membuat perencanaan energi nasional tetap bergantung pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, yang kemudian diturunkan ke Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dokumen ini, kata dia, pada dasarnya menentukan berapa besaran energi terbarukan di daerah. Termasuk potensi energi terbarukan yang ada di daerah. Kendati pada praktiknya, apa yang tertuang di dokumen dengan yang ada di lapangan kerap tidak sesuai realita.
"Saya masih menunggu turunan RUKN dan RUPTL dari presiden baru yang katanya mau sesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi delapan persen. Tapi yang terjadi adalah, proyek yang ditawarkan itu pasti proyek intensif terhadap kerusakan lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat. Karena cara yang dipakai seperti PSN," urainya.
Akibatnya, proyek-proyek energi terbarukan di daerah sering kali tidak berjalan maksimal, bahkan menimbulkan persoalan baru. Beyrra mencontohkan, proyek-proyek besar energi bersih biasanya dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana atau pengikut.
“Model PSN itu sangat sentralistik, bahkan bisa dibilang militeristik. Di banyak daerah, masyarakat lokal diusir dari lahannya atas nama pembangunan energi hijau,” ujarnya. Keputusan pembangunan energi terbarukan diambil demi memenuhi ambisi pemerintah pusat, sementara masyarakat yang tinggal di lokasi proyek justru jadi pihak paling terdampak.
Karena itu, ia menilai tata kelola energi terbarukan semestinya berlandaskan dua hal utama: transparansi dan pelibatan langsung masyarakat. Pelibatan yang dimaksud bukan sekadar partisipasi simbolik, tetapi keterlibatan nyata sejak perencanaan hingga pengelolaan. “Masyarakat harus tahu apa yang akan terjadi di masa kini dan masa depan. Mereka juga berhak menentukan bagaimana energi itu akan digunakan,” tegasnya.
Genset komunal yang saban malam meraung di Desa Mandu PS, di masa depan barangkali akan digantikan. Entah oleh listrik PLN atau berbagai "inisiatif" hijau yang ditawarkan pemerintah seperti POME dan PLTS. Namun bagi warga, istilah “energi hijau” tak banyak berarti bila kehidupan mereka tetap gelap. Program transisi energi yang digadang-gadang membawa keadilan justru terasa seperti jargon saja.
Di Mandu PS, transisi itu bak cerita yang dibawa ombak, ia terdengar di bibir pantai, tapi tak pernah sampai menjejak tanah. Sementara di lapangan, warga masih menghitung biaya solar cell yang soak, bensin untuk genset, dan waktu menyetrika sebelum listrik padam. Di tengah gencarnya wacana energi bersih, mereka masih hidup dalam lingkaran gelap, menjadi saksi bahwa transisi energi di negeri ini, sejauh ini, masih setengah hati.
Sementara hanya beberapa puluh kilometer dari desa ini, ada perusahaan tambang batu bara beroperasi 24 jam non-stop, membongkar perut bumi Kutai Timur, mengirim bongkahan batu hitam itu ke berbagai negara dan pelosok negeri. Untuk menerangi pabrik. Gedung pencakar langit. Atau bahkan pendingin ruangan yang membuat wakil rakyat nyaman duduk di kantornya.
"Saya sih kalau ada listrik, mau buat usaha rumahan. Jual wadai (istilah lokal untuk menyebut kue) kah, minum-minuman, atau buka warung kecil-kecilan," kata Harlina.
Entah sampai kapan harapan sesederhana ini mesti disimpan warga Desa Mandu PS. Di kabupaten yang kaya batu bara. Di kabupaten yang dengan bangga menyebut dirinya "The Magic Land". (*)
(*) Liputan ini bagian dari Fellowship Lokakarya Transisi Energi Berkeadilan, program kolaborasi AJI Samarinda dan Yayasan Cerah.
Related Posts
- Pengamat Kritisi Program Gratispol Khusus untuk Pejabat Eselon II, Dinilai Kurang Relevan
- Membaca Kehendak di Balik Pesan: Ketika Lingkungan Diceritakan oleh Gubernur
- Tekanan Tambang dan Sawit Terus Gerus Hutan Kaltim, Dishut Sebut Banyak Perusahaan Kayu Gulung Tikar
- Dispar Kaltim Perkuat Kesiapan Destinasi Hadapi Libur Nataru, Fokus Keamanan dan Keselamatan Wisatawan
- Formula Baru UMP 2026 Bikin Proses Melambat, Kaltim Targetkan Pengumuman Akhir Tahun